Oleh : Nofer Saputra )*
Perbedaan angka kemiskinan yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia kembali menarik perhatian publik. Selisih data ini kerap menjadi perdebatan, namun sejatinya tidak perlu dianggap sebagai pertentangan. Keduanya memiliki dasar metodologi dan tujuan yang berbeda, dan justru saling melengkapi dalam memberi gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial ekonomi suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perbedaan tersebut tidak lantas menimbulkan kebingungan atau mengganggu validitas program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.
Bank Dunia baru-baru ini memperkenalkan standar baru dalam pengukuran kemiskinan, menaikkan ambang batas garis kemiskinan ekstrem menjadi US$3 Purchasing Power Parity (PPP) per kapita per hari. Sebelumnya, standar internasional yang digunakan adalah US$2,15 PPP. Dengan standar baru tersebut, Bank Dunia memperkirakan bahwa 5,44 persen penduduk Indonesia pada 2023 berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Sementara itu, BPS yang masih menggunakan standar US$2,15 PPP mencatat angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2025 sebesar 0,85 persen.
Angka yang terlihat sangat berbeda ini bukan berarti terjadi kesalahan dalam penghitungan, melainkan mencerminkan metodologi dan tujuan yang berbeda. BPS menegaskan bahwa standar US$3 PPP yang diadopsi Bank Dunia belum secara resmi digunakan sebagai garis kemiskinan nasional karena pemerintah Indonesia masih merujuk pada rencana pembangunan yang konsisten dengan standar sebelumnya, yakni PPP 2017. Penggunaan PPP 2021 oleh Bank Dunia baru diumumkan pada Juni 2025, sedangkan Indonesia sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang masih mengacu pada PPP 2017, yakni US$2,15 PPP.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono menjelaskan bahwa BPS tetap mengikuti perkembangan global, termasuk pembaruan metode penghitungan kemiskinan. Bahkan, BPS telah mengadopsi pendekatan baru dengan menggunakan spatial deflator dalam menghitung garis kemiskinan ekstrem, menggantikan metode lama yang hanya menggunakan Consumer Price Index (CPI). Spatial deflator memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap variasi harga antarwilayah hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga data yang dihasilkan lebih relevan dalam konteks kondisi domestik Indonesia.
Selain aspek metodologis, perlu dipahami bahwa tujuan dari garis kemiskinan nasional dan internasional memang berbeda. Garis kemiskinan nasional digunakan sebagai dasar kebijakan sosial domestik, seperti penentuan sasaran bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan BPS, yaitu Cost of Basic Needs (CBN), dinilai lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Pendekatan ini mempertimbangkan struktur konsumsi lokal dan harga-harga spesifik per wilayah yang relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, garis kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia bertujuan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antarnegara dalam skala global. Pembaruan angka kemiskinan global yang dilakukan Bank Dunia lebih bertujuan untuk menilai posisi relatif Indonesia di antara negara-negara lain, bukan sebagai acuan langsung bagi kebijakan domestik. Bahkan Bank Dunia sendiri menegaskan bahwa tidak ada satu definisi tunggal mengenai kemiskinan, dan bahwa garis kemiskinan nasional tetap merupakan ukuran yang paling tepat untuk menentukan program sosial dalam negeri.
Data BPS per September 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Di luar kelompok ini, BPS juga mengelompokkan masyarakat ke dalam kategori rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Dengan demikian, BPS tidak hanya fokus pada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga memantau mobilitas kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan yang menyasar kelompok rentan yang berpotensi jatuh miskin saat terjadi gejolak ekonomi.
Dalam konteks kebijakan, validitas program-program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tidak terganggu oleh adanya perbedaan data antara BPS dan Bank Dunia. Pemerintah melalui BPS tetap memiliki pijakan kuat untuk menyusun dan menjalankan kebijakan berbasis data domestik yang komprehensif. Penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025, misalnya, menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan selama ini cukup efektif.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Nurma Midayanti juga menyampaikan bahwa BPS terus menjalin komunikasi dan konsultasi dengan Bank Dunia terkait metode penghitungan kemiskinan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari lembaga statistik nasional untuk menjaga integritas dan kredibilitas data yang digunakan pemerintah.
Penting pula dicatat bahwa peningkatan standar garis kemiskinan internasional oleh Bank Dunia tidak menunjukkan bahwa suatu negara mengalami penurunan kualitas hidup. Sebaliknya, hal itu justru mencerminkan ambisi global yang meningkat dalam menentukan standar hidup minimum. Dengan kata lain, jika lebih banyak penduduk dikategorikan miskin berdasarkan standar baru, itu mencerminkan bahwa standar kesejahteraan dunia mengalami peningkatan, bukan karena negara tersebut semakin tertinggal.
Dalam kerangka tersebut, Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan. Validitas data BPS menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan program nasional. Sedangkan data Bank Dunia tetap menjadi referensi penting dalam melihat posisi Indonesia secara global. Perbedaan metode antara kedua lembaga ini semestinya dilihat sebagai hal yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Sinergi antara data domestik dan internasional menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata.
)* Penulis adalah seorang Ekonom




.jpeg)




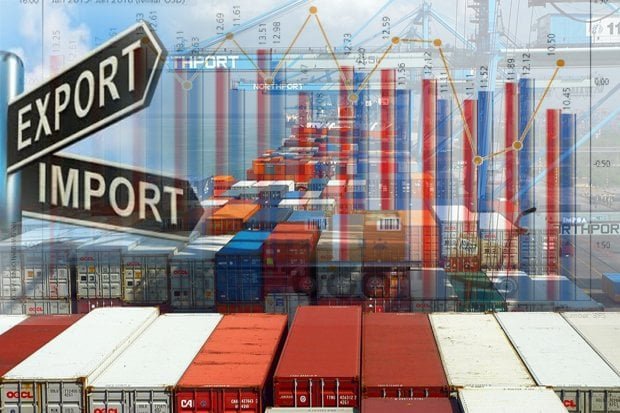


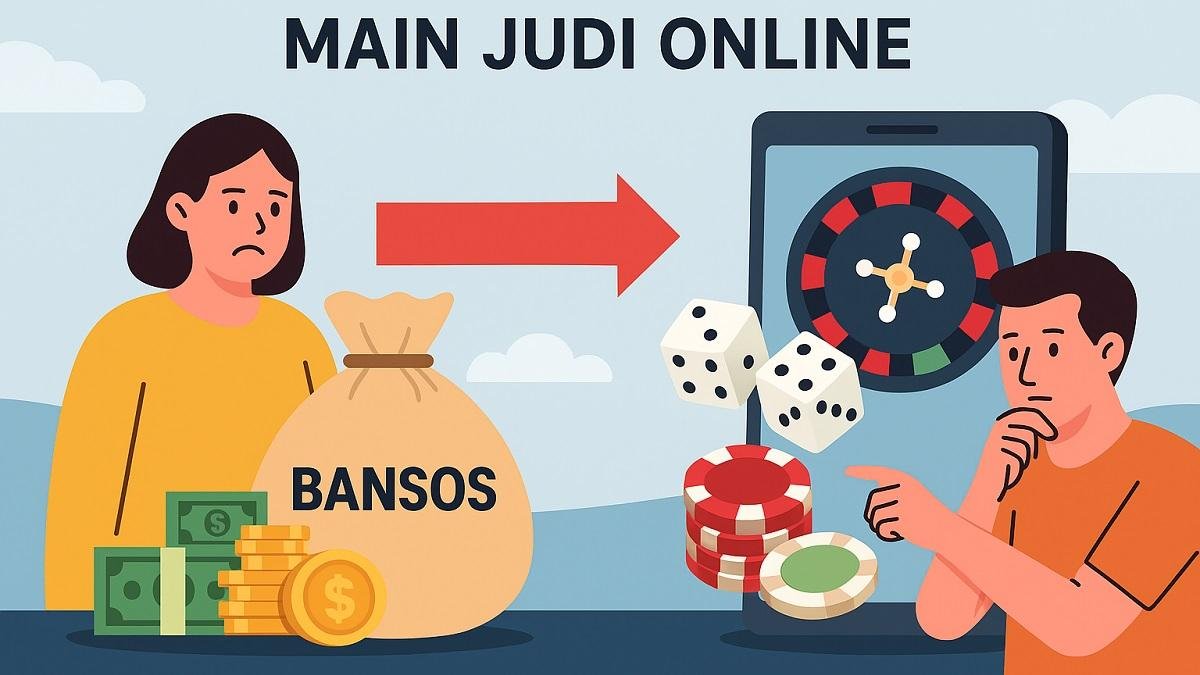
Leave a Reply